Rumah Si Pitung, Mencecap Oase Betawi di Marunda – Karina Lin
Motor ojol yang saya tumpangi, berhenti tepat di sebuah gapura komplek bangunan. Bang ojol mematikan mesin motor, saya turun dari jok motor. Rasanya lega bisa kembali menjejak di tanah setelah menempuh perjalanan yang cukup memakan waktu, ditambah panas menyengat pada Rabu siang itu.

Seorang bapak berkaus putih menghampiri, sepertinya juru parkir, dan menginstruksikan supaya motor ojol (yang mengantar saya) ditepikan agar tidak menganggu lalu lintas yang melewati pintu gapura, satu-satunya jalan masuk ke Museum Kebaharian Rumah Si Pitung di Kampung Marunda Pulo, Jakarta Utara.
Tak lama, datanglah sekuriti penjaga lokasi cagar budaya tersebut. “Pak, ini betul Rumah Si Pitung kan?” tanya saya kepadanya dan di-iya-kan olehnya. Sekitar 5 menit kemudian datang lagi seorang bapak berkemeja putih dan bercelana panjang hitam, bercakap sebentar menanyakan maksud kedatangan, lalu membimbing saya masuk ke lokasi cagar budaya Rumah Si Pitung.
Kami pun mengambil salah satu spot di bawah Rumah si Pitung, tepatnya di sela-sela pondasi. Sambil duduk lesehan dan melepas sepatu serta menikmati sejuknya angin pesisir Marunda yang berhembus, Pak Damra Hamka bercerita sekaligus meladeni berbagai pertanyaan yang saya ajukan.
Awalnya saya sempat bingung dengan Pak Damra. Ketika mengajak saya masuk ke cagar budaya Rumah Si Pitung dan duduk lesehan, saya tertanya-tanya siapakah bapak ini? Setelah duduk lesehan dan memulai percakapan, barulah saya tahu bahwa beliau merupakan guide dari Rumah Si Pitung.
***
Kisah Awal
“Obyek cagar budaya ini dibangun tahun 1880 oleh Haji Syafiuddin,” kata Pak Damra memulai cerita. Haji Syafiuddin merupakan saudagar kaya raya yang berbisnis alat-alat penangkapan ikan sehingga dijuluki saudagar sero (saudagar alat penangkap ikan).
Ia menyewakan alat-alat penangkap ikan semisal pukat raksasa. Pukat ini dibuat jadi pagar di pinggir laut, biasanya sore hari, dan pagi hari berikutnya kerumunan ikan sudah terkurung dalam pukat raksasa untuk dipanen nelayan. Nah, para nelayan di Marunda ini membayar sewa pukat kepada Haji Syafiuddin.

Tapi Haji Syafiuddin bukanlah orang Betawi.
“Beliau seorang suku Bugis dan beristrikan orang Marunda yang merupakan tuan tanah di sana,” terang Pak Damra.
Lantas kenapa rumah milik Haji Syafiuddin menjadi ‘Rumah Betawi’ dan dinamakan Rumah Si Pitung? Unsur Betawi rupanya berasal dari lokasi rumah tersebut: di daerah Marunda Pulo atau tanah Betawi.
“Pada zaman itu, rumah milik Haji Syafiuddin ini merupakan satu-satunya rumah yang ada di Marunda Pulo,” jelasnya.
Dalam perkembangannya, karena memiliki ciri khas berhubung dibangun di daerah pantai, disebut sebagai Rumah Betawi Pesisir.
Sekarang soal kedua: kenapa disebut Rumah Si Pitung?
Pak Damra menjelaskan tahun 1972 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli rumah milik Haji Syafiuddin dari keturunannya yang bernama Haji Mat Sani Bin Haji Muhammad. “Saat itu Pemprov membeli rumah ini seharga Rp 800.000,- pas tahun itu merupakan nominal yang besar,” tambahnya.
Di tangan Pemprov, rumah tersebut pernah dijadikan tempat syuting film layar lebar Si Pitung, jagoan Betawi yang dibintangi aktor tenar pada zamannya: Dicky Zulkarnain. Sebenarnya banyak sebutan selain Rumah Si Pitung, seperti Rumah Tinggi atau Rumah Langgar -karena menjadi tempat belajar mengaji untuk warga sekitar.
Tapi Rumah Si Pitung yang melekat, bukan karena jadi tempat syuting film saja. Dirunut jauh ke belakang, rumah berusia 100 tahun itu sering jadi tempat ‘ngumpet’ si Pitung, yang berubah dari nama aslinya, Ahmad Nitikusuma, karena belajar silat di perguruan silat bernama Pituan Pitung.
Jago silat itu rupanya mampir ke rumah Haji Syafiuddin untuk bersembunyi jika sedang dicari-cari Belanda. Lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau sepertinya menjadi alasan si Pitung memilih rumah Haji Syafiuddin. “Kan di sini banyak hutan bakau dan dikelilingi oleh laut. Juga dekat dengan pelabuhan. Jadi kalau mau kabur bisa melalui laut,” sambung Pak Damra
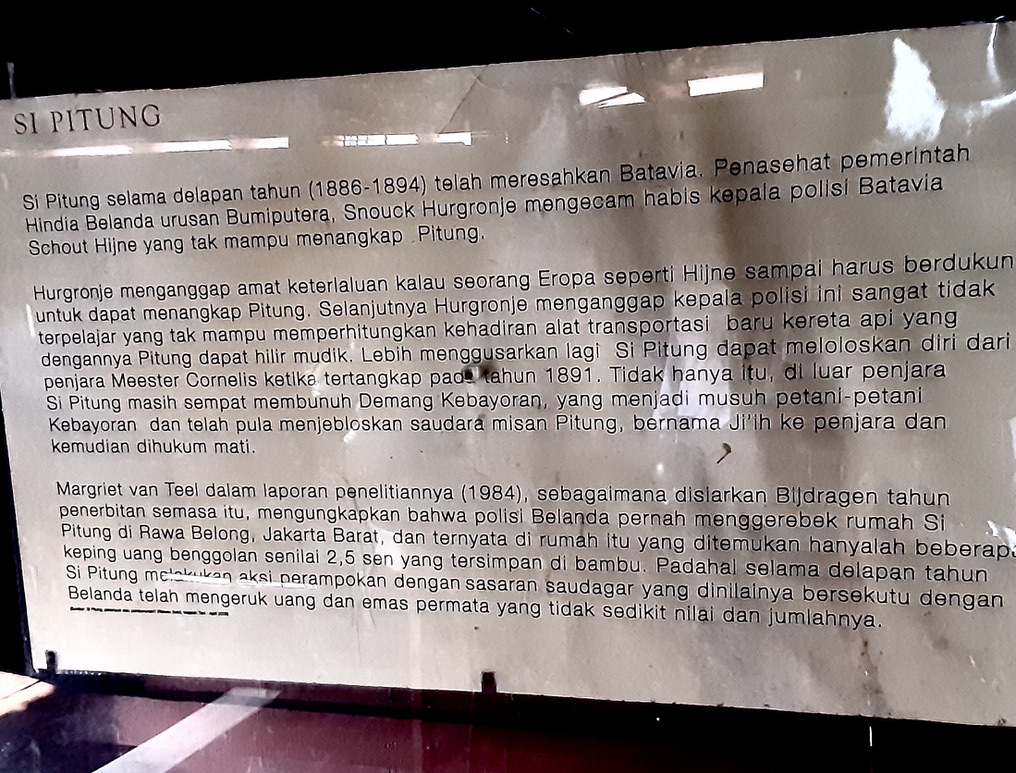
Kurang jelas hubungan Si Pitung dengan Haji Syafiuddin, namun Pak Damra mengatakan sang haji bersimpati dengan tindakan Si Pitung. “Kalau Belanda menganggap Pitung sebagai penjahat, Pak Haji mengganggapnya orang baik karena menolong yang lemah,” jelasnya.
Untuk menyamarkan jejak bahwa ia membantu Si Pitung, Haji Syafiuddin membuat skenario seolah-olah rumahnya dirampok oleh Si Pitung. Maka Pak Haji -yang sering juga berbisnis dengan Belanda- tidak dicurigai membantu penjahat yang diburu kompeni.
***
Kini
Sambil lesehan mendengar penjelasan Pak Damra, sesekali pandangan saya tersita pada aktivitas beberapa pria, yang sibuk membersihkan tiang-tiang pondasi rumah dengan sikat berkepala bulat. Satu persatu tiang pondasi dibersihkan dari debu sebelum dilap dengan kain bersih.
“Setiap hari pasti dibersihkan,” kata Sarwono, salah seorang petugas bagian pemeliharaan.

Bagaimana dengan isinya? Sama. Setiap hari disapu dan dipel sedang furniturnya sesekali dipelitur supaya tetap kinclong walau usianya terus bertambah.
Saya bisa membayangkan pekerjaan bersih-bersih harian yang melelahkan Ini sebab Rumah Si Pitung tak main-main luasnya: 500 meter persegi dalam kompleks berukuran 3.000 meter persegi. Makanya perlu beberapa orang yang gotong royong merawatnya.
Sebagian besar bangunan Rumah Pitung -pondasi, dinding, lantai- masih asli dan terbuat dari kayu ulin pilihan. “Haji Syafiuddin mendatangkan kayu ini dari Kalimantan dengan menggunakan kapalnya, kayu ulin ini merupakan kayu dengan kualitas baik, antirayap,” terang Pak Damra.
Kini ada beberapa bagian yang kayunya sudah diganti ketika direnovasi, seperti bagian pondasi untuk mengantisipasi rob di kawasan tersebut
Daerah Marunda yang lekat dengan laut dan pantai memang menjadi langganan banjir rob. Dalam satu tahun bisa terjadi tiga kali, sampai menggenangi kampung Marunda Pulo dan sekitarnya.
“Tetapi tidak semua pondasi rumah diganti. Kalau kita mengikuti peraturan mengenai bagunan cagar budaya maka ketentuannya 80% asli dan 20% baru. Namun kalau untuk rumah, semuanya masih asli kecuali furnitur yang merupakan replika yang berasal dari tahun 1972,” urainya karena yang asli rusak dimakan jaman.
Usai ‘pelajaran sejarah’ Pak Damra, saatnya masuk ke dalam Rumah Si Pitung. Kami menapak tangga di depan yang membawa ke teras yang lapang dengan seperangkat kursi dan meja kayu. Di salah satu pojok di teras itulah manekin Si Pitung seukuran tubuh manusia menyambut para wisatawan yang datang.
Di ruang tamu saya mendapati satu set kursi dan meja yang tak beda dengan di teras tadi namun salah satu merupakan kursi panjang. Meneruskan perjalanan, kami melewati selasar dan di sebelah kanannya terdapat kamar tidur Haji Syafiuddin, berukuran sekitar 3×4 meter. Ada ranjang berkelambu, satu set meja buffet, dan kaca rias di dalam kamar. Semua furnitur replika tahun 1972 itu terasa pas untuk rumah yang sudah berusia 100 tahun lebih

Perjalanan dilanjutkan dan sampailah di ruang keluarga, yang paling luas karena menjadi tempat berkumpul keluarga dan juta ruang makan. Sesudah mengulik isi rumah Si Pitung, dari depan hingga ke belakang, saya malah jadi tertanya-tanya: dimana Si Pitung bersembunyi karena hanya ada satu kamar.
Mungkin pendekar itu tidurnya suka-suka saja: di ruang tamu atau di ruang keluarga yang luas. Ternyata tidak.
“Di atas plafon kamar tidur Haji Syafiuddin itu ada tangga menuju ke atap rumah. Di situlah Pitung ngumpet sekaligus tidur,” beber Pak Damra. Ah…itu dia. Saya membayangkan tangga itu dan tempat ngumpet itu. Kalaupun Belanda datang, Si Pitung bisa kabur melalui atap.
Si Pitung bukan cuma jago silat, juga cerdik.
***
Kenangan Bersama Angin Pantai
Sekarang, kunjungan ke Rumah Si Pitung tak sulit lagi. Ada masanya orang harus menyeberang dengan perahu namun sejak tahun 2010 dibangun jembatan yang memudahkan akses masuk ke Rumah Si Pitung. Memang dikenakan tiket masuk, tapi terjangkau oleh orang banyak: dewasa Rp 5.000, pelajar Rp 2.000, dan mahasiswa Rp 3.000. Menahan diri tak minum secangkir kopi di warung saja sudah bisa beli tiket masuknya.
Sama seperti museum-museum lain, Rumah Si Pitung tutup setiap Senin setelah enam hari -Selasa hingga Minggu- kedatangan tamu sejak pukul 08.00 sampai 16.30 WIB. “Paling ramai saat akhir pekan, Sabtu dan Minggu tapi Minggu lebih ramai bisa 500an orang yang datang,” terangnya. Kebanyakan dari para pengunjung tersebut berstatus pelajar.
Di dalam kompleks, tersedia cafe yang menawarkan kuliner Betawi dan kesenian Gambang Kromong, yang tampil tiap akhir pekan.
Tak terasa, hari sudah sore. Matahari yang tadinya terik menyengat mulai redup dengan warna keorenan. Saya, sudah pasti berfoto narsis dulu, pamit dengan Pak Damra sembari berterimakasih atas kisah sejarahnya yang menemani berkeliling Rumah Si Pitung.
Mungkin salah satu cagar budaya di Jakarta ini belum banyak dikenal orang, tapi layak dikunjungi. Bukan hanya Rumah si Pitung dan kisahnya yang bisa dinimakti di sini, juga kesejukan angin pantai dan panorama laut yang melingkupi dengan pohon-pohon bakau tumbuh mengelilingi bibir lautnya. Ah sungguh membuai…
***
Karina Lin, kelahiran Tanjungkarang. Tamat dari Universitas Lampung aktif menulis dan menjadi wartawan lepas untuk berbagai media. Berpartisipasi di sejumlah buku bunga rampai, antara lain ‘Rumah Berwarna Kunyit’ (Oktober 2015), ‘Bhayangkara Lampung Melintas Badai’ (April 2016), ‘Secangkir Kopi Bumi Sekala Brak, Jejak Langkah 25 Tahun Kebangunan Lampung Barat‘ (Maret 2017) dan ‘Lampungisme: Sosiokultur, Alam ,dan Infrastruktur Bumi Ruwa Jurai’ (April 2018). Sebagai penyintas lupus, aktif dalam peningkatakan kepedulian pada penyakit SLE/Lupus dan mengelola blog semangatkarin.com.
